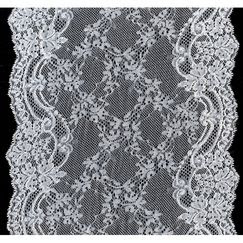I'tikaaf nya Para Wanita
Menurut jumhur ulama, tidaklah akan sah bagi seorang wanita beri'tikaaf di masjid rumahnya sendiri, karena masjid di dalam rumah tidak bisa dikatakan masjid, lagi pula keterangan yang sudah sah menerangkan bahwa para istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan i'tikaaf di Masjid Nabawi. [Lihat Fiqhus Sunnah I/402]
Tentang wanita yang beri'tikaaf di masjid diharuskan membuat kemah tersendiri dan terpisah dari laki-laki, sedangkan untuk masa sekarang harus dipikirkan tentang fitnah yang akan terjadi bila para wanita hendak i'tikaaf, yaitu terjadinya ikhtilath dengan laki-laki di tempat yang semakin banyak fitnah. Adapun soal bolehnya, para ulama membolehkan namun diusahakan untuk tidak saling pandang antara laki-laki dan wanita. [Lihat al-Mughni IV/464-465, baca Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram III/260.]
WAKTU MEMULAI DAN MENGAKHIRI I'TIKAAF
Pada pembahasan yang lalu telah disebutkan bahwa waktu i'tikaaf sunnat adalah tidak terbatas. Maka, apabila seseorang telah masuk masjid dan berniat taqarrub kepada Allah dengan tinggal di dalam masjid beribadah beberapa saat, berarti ia beri'tikaaf sampai ia keluar.
Dan jika seseorang berniat hendak i'tikaaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, maka hendaklah ia mulai memasuki masjid sebelum matahari terbenam.
Pendapat yang menerangkan bahwa waktu dimulainya i'tikaaf adalah sebelum matahari terbenam pada tanggal 20 Ramadhan, yaitu pada malam ke 21, merupakan pendapat dari Imam Malik, Imam Hanafi, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya.
Lihat Syarah Muslim VIII/68, Majmu' Syarhul Muhadzdzab VI/492, Fathul Baary IV/277, al-Mughni IV/489-490 dan Bidayatul Mujtahid I/230.
Dalil mereka ialah riwayat tentang i'tikaafnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di awal Ramadhan, pertengahan dan akhir Ramadhan:
عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ اْلأَوَاخِرَ.
"Dari Abu Sa'id al-Khudri Radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang hendak beri'tikaaf bersamaku, hendaklah ia melakukannya pada sepuluh malam terakhir (dari bulan Ramadhan)". [HSR. Al-Bukhari no. 2027.]
Maksud "sepuluh terakhir", adalah nama bilangan malam, dan bermula pada malam kedua puluh satu atau malam kedua puluh. [Lihat Fiqhus Sunnah I/403.]
Tentang hadits 'Aisyah:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ
"Dari 'Aisyah Radhiyallahu anha, ia berkata: "Adalah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam apabila hendak i'tikaaf, beliau shalat Shubuh dulu, kemudian masuk ke tempat i'tikaaf" [HSR. Al-Bukhari no. 2033 dan Muslim no. 1173]
Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa permulaan dari waktu i'tikaaf itu adalah di permulaan siang. Ini menurut pendapat al-Auza'i, al Laits dan ats-Tsauri. [Lihat Nailul Authar IV/296.]
Maksud dari hadits Aisyah di atas ialah, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam masuk ke tempat yang sudah disediakan untuk i'tikaaf di masjid setelah beliau selesai mengerjakan shalat Shubuh. Jadi, bukan masuk masjidnya ba'da Shubuh.
Adapun masuk ke masjid untuk i'tikaaf tetap di awal malam sebelum terbenamnya matahari. Wallaahu a'lam bish shawaab [Lihat Fiqhus Sunnah I/403.]
Mengenai waktu keluar dari masjid setelah selesai menjalankan i'tikaaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i waktunya adalah sesudah matahari terbenam (di akhir Ramadhan). Sedangkan menurut Imam Ahmad rahimahullah, ia disunnahkan untuk tinggal di masjid sampai waktu shalat 'Idul Fitri. Jadi, keluar dari masjid ketika ia keluar menuju lapangan untuk mengerjakan shalat 'Ied. Akan tetapi menurut mereka boleh pula keluar dari masjid setelah matahari terbenam. [Lihat Bidaayatul Mujtahid (I/230) dan al-Mughni (IV/490).]
Jadi kesimpulannya, empat Imam telah sepakat bahwa waktu i'tikaaf berakhir dengan terbenamnya matahari di akhir Ramadhan.
Ibrahim an-Nakha'i berkata, "Mereka menganggap sunnah bermalam di masjid pada malam 'Idul Fitri bagi orang yang beri'tikaaf pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan, kemudian pagi harinya langsung pergi ke lapangan (untuk shalat Idul Fitri)". [Baca al-Mughni, IV/490-491.]
Dan orang yang bernadzar akan beri'tikaaf satu hari atau beberapa hari tertentu, atau bermaksud melaksanakan i'tikaaf sunnat, maka hendaklah ia memulai i'tikaafnya itu sebelum terbit fajar, dan keluar dari masjid bila matahari sudah terbenam, baik i'tikaaf itu di bulan Ramadhan maupun di bulan lainnya. [Lihat Bidaayatul Mujtahid, I/230, al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab VI/494, Fiqhus Suunah I/403-404.]
Ibnu Hazm berkata, "Orang yang bernadzar hendak i'tikaaf satu malam atau beberapa malam tertentu, atau ia hendak melaksanakan i'tikaaf sunnat, maka hendaklah ia masuk ke masjid sebelum terbenam matahari, dan keluar dari masjid bila sudah terlihat terbitnya fajar. Sebabnya karena permulaan malam ialah saat yang mengiringi terbenamnya matahari, dan ia berakhir dengan terbitnya fajar. Sedangkan permulaan siang adalah waktu terbitnya fajar dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Dan seseorang tidak dibebani kewajiban melainkan menurut apa yang telah diikrarkan dan diniatkannya". [Lihat al-Muhalla V/198, masalah no. 636.]
HAL-HAL YANG SUNNAT DAN YANG MAKRUH BAGI ORANG YANG I'TIKAAF
Disunnatkan bagi orang yang i'tikaaf memperbanyak ibadah sunnat serta menyibukkan diri dengan shalat berjama'ah dan shalat-shalat sunnat, membaca al-Qur'an, tasbih, tahmid, takbir, istighfar, berdo'a membaca shalawat atas Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan ibadah-ibadah lain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Semua ibadah ini harus dilakukan sesuai dengan Sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.
Termasuk juga dalam hal ini disunnahkan menuntut ilmu, membaca/menelaah kitab-kitab tafsir dan hadits, membaca riwayat para Nabi 'alaihimush shalatu wa sallam dan orang-orang shalih, dan mempelajari kitab-kitab fiqh serta kitab-kitab yang berisi tentang masalah aqidah dan tauhid.
Dimakruhkan bagi orang yang i'tikaaf melakukan hal-hal yang tidak perlu dan tidak bermanfaat, baik berupa perkataan atau perbuatan, sabda beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam
مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ.
"Diantara kebaikan Islam seseorang ialah, ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna". [HR. At-Tirmidzi no. 2317, Ibnu Majah no. 3976 dari Shahabat Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu. Dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di Shahiih Jami'us Shaghiir no. 5911]
Dimakruhkan pula menahan diri dari berbicara, yakni seseorang tidak mau bicara, karena mengira bahwa hal itu mendekatkan diri kepada Allah Azza Wa Jalla.
Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhu berkata: "Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sedang khutbah, tampak oleh beliau seorang laki-laki yang tetap berdiri (di terik matahari). Maka beliau bertanya (kepada para Shahabat): 'Siapakah orang itu?' Para Shahabat menjawab: 'Namanya Abu Israil, ia bernadzar akan terus berdiri, tidak akan duduk, tidak mau bernaung dan tidak mau berbicara serta akan terus berpuasa'. Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
"Suruhlah ia berbicara, bernaung dan duduk, dan hendaklah ia meneruskan puasanya". [HSR. Al-Bukhari no. 6704, Abu Dawud no. 3300, ath-Thahawi di dalam kitab Musykilul Atsaar III/44 dan al-Baihaqi X/75.]
HAL-HAL YANG MEMBATALKAN I'TIKAAF
Pertama:
Sengaja keluar dari masjid tanpa suatu keperluan walaupun hanya sebentar. Keluar dari masjid akan menjadikan batal i'tikaafnya, karena tinggal di masjid sebagai rukun i'tikaaf.
Kedua:
Murtad karena bertentangan dengan makna ibadah, dan juga berdasarkan firman Allah:
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
"Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada-mu dan kepada (Nabi-Nabi) yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan (Rabb), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu ter-masuk orang-orang yang merugi". [Az- Zumar : 65]
Ketiga: Hilang akal disebabkan gila atau mabuk.
Keempat: Haidh.
Kelima: Nifas.
Keenam: Bersetubuh/bersenggama, berdasarkan firman Allah Subahanhu wa Ta'ala
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka, sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa". [Al-Baqarah: 187] [Lihat Fiqhus Sunnah I/406]
Menurut pendapat Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'anhu: "Apabila seorang mu'takif (yang i'tikaaf) bersetubuh, maka batal i'tikaafnya dan ia mulai dari awal lagi.[Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq, dengan sanad yang shahih. Lihat Qiyamur Ramadhan hal. 41 oleh Imam al-Albani]
HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN SEWAKTU I'TIKAAF
Pertama:
I'tikaafnya seorang wanita dan kunjungannya kepada suaminya yang beri'tikaaf di dalam masjid.
Diperbolehkan bagi seorang wanita untuk mengunjungi suaminya yang tengah beri'tikaaf. Dan suaminya yang sedang beri'tikaaf diperbolehkan untuk mengantar-kannya sampai pintu masjid.
Shafiyyah Radhiyallahu anha bercerita: "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah beri'tikaaf (pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan), lalu aku datang untuk mengunjungi beliau pada malam hari, (yang saat itu di sisi beliau sudah ada beberapa istrinya, lalu mereka pergi). Kemudian aku berbicara dengan beliau beberapa saat, untuk selanjutnya aku berdiri untuk kembali. (Maka beliau bersabda: 'Janganlah kamu tergesa-gesa, biar aku mengantarmu'). Kemudian beliau berdiri mengantarku -dan rumah Shafiyyah di rumah Usamah bin Zaid-. Sehingga ketika sampai di pintu masjid yang tidak jauh dari pintu Ummu Salamah, tiba-tiba ada dua orang dari kaum Anshar yang melintas. Ketika melihat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, kedua orang itu mempercepat jalannya, maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Janganlah kalian tergesa-gesa, sesungguhnya dia adalah Shafiyyah binti Huyay'. Kemudian keduanya menjawab: 'Mahasuci Allah, wahai Rasulullah'. Beliau bersabda: 'Sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam diri manusia seperti aliran darah. Dan sesungguhnya aku khawatir syaitan itu akan melontarkan kejahatan dalam hati kalian berdua, atau beliau bersabda (melontarkan sesuatu)'". [HR. Al-Bukhari no. 2035, Muslim no. 2175]
Kedua:
Menyisir rambut, berpangkas, memotong kuku, membersihkan tubuh, memakai pakaian terbaik dan memakai wangi-wangian.
Ketiga:
Keluar untuk sesuatu keperluan yang tidak dapat dielakkan.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِيْ حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ اْلإِنْسَانِ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا
"Dari Aisyah Radhiyalahu 'anha, bahwa ia pernah menyisir rambut Nabi Shallallahu alaihi wa sallam padahal ia (Aisyah) sedang haidh, dan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam sedang beri'tikaaf di masjid. Aisyah berada di dalam kamarnya dan kepala Nabi Shallallahu alaihi wa sallam dimasukkan ke kamar Aisyah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bila sedang beri'tikaaf tidak pernah masuk rumah melainkan kalau untuk menunaikan hajat. [HSR. Al-Bukhari no. 2029, 2046, Muslim no. 297 (6-7), Abu Dawud no. 2467, at-Tirmidzi no. 804, Ibnu Majah no. 1776 dan 1778, Malik I/257 no. 1, Ibnul Jarud no. 409 dan Ahmad VI/104, 181, 235, 247, 262.]
Berkata Ibnul Mundzir: "Para ulama sepakat, bahwa orang yang i'tikaaf boleh keluar dari masjid (tempat i'tikaafnya) untuk keperluan buang air besar atau kencing, karena hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, (apabila tidak ada kamar mandi/wc di masjid -pent.). Dalam hal ini, sama hukumnya dengan kebutuhan makan minum bila tidak ada yang mengantarnya, maka boleh ia keluar (sekedarnya)".[Lihat Fiqhus Sunnah I/405.]
Aisyah Radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwa ia tidak menjenguk orang sakit ketika sedang i'tikaaf melainkan hanya sambil lewat saja, misalnya ada orang sakit di dalam rumah, ia bertanya kepada si sakit sambil lewat saja. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari dan Muslim.
KHATIMAH
Dianjurkan bagi orang-orang yang ber-i’tikaaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan dan yang tidak i’tikaaf, berusa-halah memanfaatkan waktu untuk ibadah kepada Allah, perbanyaklah baca al-Qur-an, berdzikir kepada Allah, dan melakukan shalat-shalat sunnat yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, mudah-mudahan kita ter-masuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar yang keutamaannya lebih baik dari seribu bulan dan mudah-mudahan pula dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ {1} وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ {2} لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ {3} تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ {4} سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ {5}
“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur'an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun Malaikat-Malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.” [Al-Qadar: 1-5]
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدَرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .
“Barangsiapa berdiri (melaksanakan ibadah) pada malam Lailatul Qadar, karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” [HSR. Al-Bukhari no. 2014, Muslim 760 (175), Abu Dawud no. 1372, an-Nasaa-i IV/157]
Dianjurkan pula banyak do’a dan dzikir ini pada malam ganjil di akhir Ramadhan yang diharapkan adanya Lailatul Qadar:
اللّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.
“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan, maka maaf-kanlah aku. [HSR. Ahmad VI/171, Ibnu Majah no. 3850, at-Tirmidzi no. 3513 dari ‘Aisyah d. Lihat Shahih at-Tirmidzi no. 2789 dan Shahih Ibni Majah no. 3105.]
Wallahu a’lam bish shawaab.
Penutup dari pembahasan ini adalah do’a:
سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.
Mahasuci Engkau, ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang berhak untuk diibadahi dengan benar) ke-cuali Engkau, aku meminta ampun dan ber-taubat kepada-Mu.[HR. An-Nasa-i di dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 403, Ahmad VI/77. Lihat Fat-hul Baari XIII/546, Silsilah al-Ahaadits ash-Shahihah no. 3164.]
Maraji'
1. Shahih al-Bukhari.
2. Shahih Muslim tarqim Muhammad Fuad Abdul Baqi.
3. Fat-hul Baary Syarah Shahih Bukhari oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalaany, cet. Daarul Fikr.
4. Syarah Shahih Muslim oleh Imam an-Nawawy, cet. Daarul Fikr.
5. Sunan Abu Dawud.
6. Jaami' at-Tirmidzi.
7. Sunan Ibni Majah.
8. Sunan an-Nasaa'i.
9. Musnad Imam Ahmad, cet. Daarul Fikr.
10. Al-Muwaththa' Imam Malik, tarqim Mu-hammad Fuad 'Abdul Baqi, cet. Darul Hadits thn. 1371, Cairo.
11. As-Sunan al-Kubra Imam al-Baihaqy, cet. Daarul Ma'rifah.
12. Sunan ad-Darimi, cet. Daarul Fikr.
13. Shahih Ibnu Majah bil Ikhtisharis Sanad, oleh Imam Muhammad Nashiruddin al-Albani, al-maktabah at-Tarbiyah al-'Araby lid Duwal al-Khalij, thn. 1408.
14. Shahih at-Tirmidzi.
15. Al-Muntaqa, oleh Ibnul Jarud, cet. Daarul Kutub al-Ilmiyyah.
16. Silsilah al-Ahaadits ash-Shahiihah, oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.
17. Shahih Jaami'ush Shaghiir, oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.
18. Al-Muhalla, Ibnu Hazm, cet. Daarul Fikr.
19. Zaadul Ma'ad Fii Hadyi Khairil 'Ibaad, oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Tahqiq dan takhrij Syu'aib al-Arnauth dan Abdul Qadir al-Arnauth.
20. Al-Mughni, oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdil Muhsin at-Turky.
21.Nailul Authar, oleh Imam asy-Syaukani, cet. Mathba'ah Musthafa al-Baabi al-Halabi, Mesir.
22. Subulus Salam, Imam ash-Shan'any.
23. Irwaa'ul Ghalil fit Takhrij Ahaadits Manaris Sabil, oleh Syaikh Muhammad Nashirud-din al-Albani.
24. Fiqhus Sunnah, Sayyid Sabiq, cet. III Daar al-Fikr, th. 1403 H.
25. Bidaayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd, cet. Daarul Fikr.
26. Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, oleh Imam Nawawi, cet. Daarul Fikr.
27. Fiqhul Islam Syarah Bulughil Maram, oleh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi.
28. Qiyaamu Ramadhaan, oleh Syaikh Mu-hammad Nashiruddin al-Albani.
29. Al-Inshaf fii Ahkamil I'tikaaf, oleh Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid.
30. Amalul Yaumi wal Lailah, oleh Imam an-Nasa'i.
31. Al-Jami' li Ahkaamil Qur'an, oleh Imam al-Qurthubi.
32. Ahkaamul Qur'an, oleh al-Jashshash.
33. Rawaa'iul Bayan fii Tafsiri Ayatil Ahkam.
34. Lisaanul Arab, oleh Ibnu Manzhur, cet. Daar Ihyaa-it Turats al-Araby.
35. An-Nihayah fii Ghariibil Hadits, oleh Ibnul Atsiir.
36. Mufradaat Alfaazhil Qur-aan, ar-Raaghib al-Ashfahaani.
37. Shahih Sunan Abi Dawud, jilid II, oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany
[Disalin dari buku I'tikaaf, Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit Pustaka Abdullah, Gedung TEMPO Jl Utan Panjang Raya No. 64 - Jakarta Pusat, Cetakan Pertama Ramadhan 1425H/Oktober 2004M]
sumber: almanhaj.or.id
Tentang wanita yang beri'tikaaf di masjid diharuskan membuat kemah tersendiri dan terpisah dari laki-laki, sedangkan untuk masa sekarang harus dipikirkan tentang fitnah yang akan terjadi bila para wanita hendak i'tikaaf, yaitu terjadinya ikhtilath dengan laki-laki di tempat yang semakin banyak fitnah. Adapun soal bolehnya, para ulama membolehkan namun diusahakan untuk tidak saling pandang antara laki-laki dan wanita. [Lihat al-Mughni IV/464-465, baca Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram III/260.]
WAKTU MEMULAI DAN MENGAKHIRI I'TIKAAF
Pada pembahasan yang lalu telah disebutkan bahwa waktu i'tikaaf sunnat adalah tidak terbatas. Maka, apabila seseorang telah masuk masjid dan berniat taqarrub kepada Allah dengan tinggal di dalam masjid beribadah beberapa saat, berarti ia beri'tikaaf sampai ia keluar.
Dan jika seseorang berniat hendak i'tikaaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, maka hendaklah ia mulai memasuki masjid sebelum matahari terbenam.
Pendapat yang menerangkan bahwa waktu dimulainya i'tikaaf adalah sebelum matahari terbenam pada tanggal 20 Ramadhan, yaitu pada malam ke 21, merupakan pendapat dari Imam Malik, Imam Hanafi, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya.
Lihat Syarah Muslim VIII/68, Majmu' Syarhul Muhadzdzab VI/492, Fathul Baary IV/277, al-Mughni IV/489-490 dan Bidayatul Mujtahid I/230.
Dalil mereka ialah riwayat tentang i'tikaafnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di awal Ramadhan, pertengahan dan akhir Ramadhan:
عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ اْلأَوَاخِرَ.
"Dari Abu Sa'id al-Khudri Radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang hendak beri'tikaaf bersamaku, hendaklah ia melakukannya pada sepuluh malam terakhir (dari bulan Ramadhan)". [HSR. Al-Bukhari no. 2027.]
Maksud "sepuluh terakhir", adalah nama bilangan malam, dan bermula pada malam kedua puluh satu atau malam kedua puluh. [Lihat Fiqhus Sunnah I/403.]
Tentang hadits 'Aisyah:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ
"Dari 'Aisyah Radhiyallahu anha, ia berkata: "Adalah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam apabila hendak i'tikaaf, beliau shalat Shubuh dulu, kemudian masuk ke tempat i'tikaaf" [HSR. Al-Bukhari no. 2033 dan Muslim no. 1173]
Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa permulaan dari waktu i'tikaaf itu adalah di permulaan siang. Ini menurut pendapat al-Auza'i, al Laits dan ats-Tsauri. [Lihat Nailul Authar IV/296.]
Maksud dari hadits Aisyah di atas ialah, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam masuk ke tempat yang sudah disediakan untuk i'tikaaf di masjid setelah beliau selesai mengerjakan shalat Shubuh. Jadi, bukan masuk masjidnya ba'da Shubuh.
Adapun masuk ke masjid untuk i'tikaaf tetap di awal malam sebelum terbenamnya matahari. Wallaahu a'lam bish shawaab [Lihat Fiqhus Sunnah I/403.]
Mengenai waktu keluar dari masjid setelah selesai menjalankan i'tikaaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i waktunya adalah sesudah matahari terbenam (di akhir Ramadhan). Sedangkan menurut Imam Ahmad rahimahullah, ia disunnahkan untuk tinggal di masjid sampai waktu shalat 'Idul Fitri. Jadi, keluar dari masjid ketika ia keluar menuju lapangan untuk mengerjakan shalat 'Ied. Akan tetapi menurut mereka boleh pula keluar dari masjid setelah matahari terbenam. [Lihat Bidaayatul Mujtahid (I/230) dan al-Mughni (IV/490).]
Jadi kesimpulannya, empat Imam telah sepakat bahwa waktu i'tikaaf berakhir dengan terbenamnya matahari di akhir Ramadhan.
Ibrahim an-Nakha'i berkata, "Mereka menganggap sunnah bermalam di masjid pada malam 'Idul Fitri bagi orang yang beri'tikaaf pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan, kemudian pagi harinya langsung pergi ke lapangan (untuk shalat Idul Fitri)". [Baca al-Mughni, IV/490-491.]
Dan orang yang bernadzar akan beri'tikaaf satu hari atau beberapa hari tertentu, atau bermaksud melaksanakan i'tikaaf sunnat, maka hendaklah ia memulai i'tikaafnya itu sebelum terbit fajar, dan keluar dari masjid bila matahari sudah terbenam, baik i'tikaaf itu di bulan Ramadhan maupun di bulan lainnya. [Lihat Bidaayatul Mujtahid, I/230, al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab VI/494, Fiqhus Suunah I/403-404.]
Ibnu Hazm berkata, "Orang yang bernadzar hendak i'tikaaf satu malam atau beberapa malam tertentu, atau ia hendak melaksanakan i'tikaaf sunnat, maka hendaklah ia masuk ke masjid sebelum terbenam matahari, dan keluar dari masjid bila sudah terlihat terbitnya fajar. Sebabnya karena permulaan malam ialah saat yang mengiringi terbenamnya matahari, dan ia berakhir dengan terbitnya fajar. Sedangkan permulaan siang adalah waktu terbitnya fajar dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Dan seseorang tidak dibebani kewajiban melainkan menurut apa yang telah diikrarkan dan diniatkannya". [Lihat al-Muhalla V/198, masalah no. 636.]
HAL-HAL YANG SUNNAT DAN YANG MAKRUH BAGI ORANG YANG I'TIKAAF
Disunnatkan bagi orang yang i'tikaaf memperbanyak ibadah sunnat serta menyibukkan diri dengan shalat berjama'ah dan shalat-shalat sunnat, membaca al-Qur'an, tasbih, tahmid, takbir, istighfar, berdo'a membaca shalawat atas Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan ibadah-ibadah lain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Semua ibadah ini harus dilakukan sesuai dengan Sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.
Termasuk juga dalam hal ini disunnahkan menuntut ilmu, membaca/menelaah kitab-kitab tafsir dan hadits, membaca riwayat para Nabi 'alaihimush shalatu wa sallam dan orang-orang shalih, dan mempelajari kitab-kitab fiqh serta kitab-kitab yang berisi tentang masalah aqidah dan tauhid.
Dimakruhkan bagi orang yang i'tikaaf melakukan hal-hal yang tidak perlu dan tidak bermanfaat, baik berupa perkataan atau perbuatan, sabda beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam
مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ.
"Diantara kebaikan Islam seseorang ialah, ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna". [HR. At-Tirmidzi no. 2317, Ibnu Majah no. 3976 dari Shahabat Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu. Dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di Shahiih Jami'us Shaghiir no. 5911]
Dimakruhkan pula menahan diri dari berbicara, yakni seseorang tidak mau bicara, karena mengira bahwa hal itu mendekatkan diri kepada Allah Azza Wa Jalla.
Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhu berkata: "Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sedang khutbah, tampak oleh beliau seorang laki-laki yang tetap berdiri (di terik matahari). Maka beliau bertanya (kepada para Shahabat): 'Siapakah orang itu?' Para Shahabat menjawab: 'Namanya Abu Israil, ia bernadzar akan terus berdiri, tidak akan duduk, tidak mau bernaung dan tidak mau berbicara serta akan terus berpuasa'. Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
"Suruhlah ia berbicara, bernaung dan duduk, dan hendaklah ia meneruskan puasanya". [HSR. Al-Bukhari no. 6704, Abu Dawud no. 3300, ath-Thahawi di dalam kitab Musykilul Atsaar III/44 dan al-Baihaqi X/75.]
HAL-HAL YANG MEMBATALKAN I'TIKAAF
Pertama:
Sengaja keluar dari masjid tanpa suatu keperluan walaupun hanya sebentar. Keluar dari masjid akan menjadikan batal i'tikaafnya, karena tinggal di masjid sebagai rukun i'tikaaf.
Kedua:
Murtad karena bertentangan dengan makna ibadah, dan juga berdasarkan firman Allah:
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
"Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada-mu dan kepada (Nabi-Nabi) yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan (Rabb), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu ter-masuk orang-orang yang merugi". [Az- Zumar : 65]
Ketiga: Hilang akal disebabkan gila atau mabuk.
Keempat: Haidh.
Kelima: Nifas.
Keenam: Bersetubuh/bersenggama, berdasarkan firman Allah Subahanhu wa Ta'ala
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka, sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa". [Al-Baqarah: 187] [Lihat Fiqhus Sunnah I/406]
Menurut pendapat Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'anhu: "Apabila seorang mu'takif (yang i'tikaaf) bersetubuh, maka batal i'tikaafnya dan ia mulai dari awal lagi.[Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq, dengan sanad yang shahih. Lihat Qiyamur Ramadhan hal. 41 oleh Imam al-Albani]
HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN SEWAKTU I'TIKAAF
Pertama:
I'tikaafnya seorang wanita dan kunjungannya kepada suaminya yang beri'tikaaf di dalam masjid.
Diperbolehkan bagi seorang wanita untuk mengunjungi suaminya yang tengah beri'tikaaf. Dan suaminya yang sedang beri'tikaaf diperbolehkan untuk mengantar-kannya sampai pintu masjid.
Shafiyyah Radhiyallahu anha bercerita: "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah beri'tikaaf (pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan), lalu aku datang untuk mengunjungi beliau pada malam hari, (yang saat itu di sisi beliau sudah ada beberapa istrinya, lalu mereka pergi). Kemudian aku berbicara dengan beliau beberapa saat, untuk selanjutnya aku berdiri untuk kembali. (Maka beliau bersabda: 'Janganlah kamu tergesa-gesa, biar aku mengantarmu'). Kemudian beliau berdiri mengantarku -dan rumah Shafiyyah di rumah Usamah bin Zaid-. Sehingga ketika sampai di pintu masjid yang tidak jauh dari pintu Ummu Salamah, tiba-tiba ada dua orang dari kaum Anshar yang melintas. Ketika melihat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, kedua orang itu mempercepat jalannya, maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Janganlah kalian tergesa-gesa, sesungguhnya dia adalah Shafiyyah binti Huyay'. Kemudian keduanya menjawab: 'Mahasuci Allah, wahai Rasulullah'. Beliau bersabda: 'Sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam diri manusia seperti aliran darah. Dan sesungguhnya aku khawatir syaitan itu akan melontarkan kejahatan dalam hati kalian berdua, atau beliau bersabda (melontarkan sesuatu)'". [HR. Al-Bukhari no. 2035, Muslim no. 2175]
Kedua:
Menyisir rambut, berpangkas, memotong kuku, membersihkan tubuh, memakai pakaian terbaik dan memakai wangi-wangian.
Ketiga:
Keluar untuk sesuatu keperluan yang tidak dapat dielakkan.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِيْ حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ اْلإِنْسَانِ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا
"Dari Aisyah Radhiyalahu 'anha, bahwa ia pernah menyisir rambut Nabi Shallallahu alaihi wa sallam padahal ia (Aisyah) sedang haidh, dan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam sedang beri'tikaaf di masjid. Aisyah berada di dalam kamarnya dan kepala Nabi Shallallahu alaihi wa sallam dimasukkan ke kamar Aisyah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bila sedang beri'tikaaf tidak pernah masuk rumah melainkan kalau untuk menunaikan hajat. [HSR. Al-Bukhari no. 2029, 2046, Muslim no. 297 (6-7), Abu Dawud no. 2467, at-Tirmidzi no. 804, Ibnu Majah no. 1776 dan 1778, Malik I/257 no. 1, Ibnul Jarud no. 409 dan Ahmad VI/104, 181, 235, 247, 262.]
Berkata Ibnul Mundzir: "Para ulama sepakat, bahwa orang yang i'tikaaf boleh keluar dari masjid (tempat i'tikaafnya) untuk keperluan buang air besar atau kencing, karena hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, (apabila tidak ada kamar mandi/wc di masjid -pent.). Dalam hal ini, sama hukumnya dengan kebutuhan makan minum bila tidak ada yang mengantarnya, maka boleh ia keluar (sekedarnya)".[Lihat Fiqhus Sunnah I/405.]
Aisyah Radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwa ia tidak menjenguk orang sakit ketika sedang i'tikaaf melainkan hanya sambil lewat saja, misalnya ada orang sakit di dalam rumah, ia bertanya kepada si sakit sambil lewat saja. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari dan Muslim.
KHATIMAH
Dianjurkan bagi orang-orang yang ber-i’tikaaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan dan yang tidak i’tikaaf, berusa-halah memanfaatkan waktu untuk ibadah kepada Allah, perbanyaklah baca al-Qur-an, berdzikir kepada Allah, dan melakukan shalat-shalat sunnat yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, mudah-mudahan kita ter-masuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar yang keutamaannya lebih baik dari seribu bulan dan mudah-mudahan pula dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ {1} وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ {2} لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ {3} تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ {4} سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ {5}
“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur'an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun Malaikat-Malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.” [Al-Qadar: 1-5]
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدَرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .
“Barangsiapa berdiri (melaksanakan ibadah) pada malam Lailatul Qadar, karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” [HSR. Al-Bukhari no. 2014, Muslim 760 (175), Abu Dawud no. 1372, an-Nasaa-i IV/157]
Dianjurkan pula banyak do’a dan dzikir ini pada malam ganjil di akhir Ramadhan yang diharapkan adanya Lailatul Qadar:
اللّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.
“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan, maka maaf-kanlah aku. [HSR. Ahmad VI/171, Ibnu Majah no. 3850, at-Tirmidzi no. 3513 dari ‘Aisyah d. Lihat Shahih at-Tirmidzi no. 2789 dan Shahih Ibni Majah no. 3105.]
Wallahu a’lam bish shawaab.
Penutup dari pembahasan ini adalah do’a:
سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.
Mahasuci Engkau, ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang berhak untuk diibadahi dengan benar) ke-cuali Engkau, aku meminta ampun dan ber-taubat kepada-Mu.[HR. An-Nasa-i di dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 403, Ahmad VI/77. Lihat Fat-hul Baari XIII/546, Silsilah al-Ahaadits ash-Shahihah no. 3164.]
Maraji'
1. Shahih al-Bukhari.
2. Shahih Muslim tarqim Muhammad Fuad Abdul Baqi.
3. Fat-hul Baary Syarah Shahih Bukhari oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalaany, cet. Daarul Fikr.
4. Syarah Shahih Muslim oleh Imam an-Nawawy, cet. Daarul Fikr.
5. Sunan Abu Dawud.
6. Jaami' at-Tirmidzi.
7. Sunan Ibni Majah.
8. Sunan an-Nasaa'i.
9. Musnad Imam Ahmad, cet. Daarul Fikr.
10. Al-Muwaththa' Imam Malik, tarqim Mu-hammad Fuad 'Abdul Baqi, cet. Darul Hadits thn. 1371, Cairo.
11. As-Sunan al-Kubra Imam al-Baihaqy, cet. Daarul Ma'rifah.
12. Sunan ad-Darimi, cet. Daarul Fikr.
13. Shahih Ibnu Majah bil Ikhtisharis Sanad, oleh Imam Muhammad Nashiruddin al-Albani, al-maktabah at-Tarbiyah al-'Araby lid Duwal al-Khalij, thn. 1408.
14. Shahih at-Tirmidzi.
15. Al-Muntaqa, oleh Ibnul Jarud, cet. Daarul Kutub al-Ilmiyyah.
16. Silsilah al-Ahaadits ash-Shahiihah, oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.
17. Shahih Jaami'ush Shaghiir, oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.
18. Al-Muhalla, Ibnu Hazm, cet. Daarul Fikr.
19. Zaadul Ma'ad Fii Hadyi Khairil 'Ibaad, oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Tahqiq dan takhrij Syu'aib al-Arnauth dan Abdul Qadir al-Arnauth.
20. Al-Mughni, oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdil Muhsin at-Turky.
21.Nailul Authar, oleh Imam asy-Syaukani, cet. Mathba'ah Musthafa al-Baabi al-Halabi, Mesir.
22. Subulus Salam, Imam ash-Shan'any.
23. Irwaa'ul Ghalil fit Takhrij Ahaadits Manaris Sabil, oleh Syaikh Muhammad Nashirud-din al-Albani.
24. Fiqhus Sunnah, Sayyid Sabiq, cet. III Daar al-Fikr, th. 1403 H.
25. Bidaayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd, cet. Daarul Fikr.
26. Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, oleh Imam Nawawi, cet. Daarul Fikr.
27. Fiqhul Islam Syarah Bulughil Maram, oleh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi.
28. Qiyaamu Ramadhaan, oleh Syaikh Mu-hammad Nashiruddin al-Albani.
29. Al-Inshaf fii Ahkamil I'tikaaf, oleh Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid.
30. Amalul Yaumi wal Lailah, oleh Imam an-Nasa'i.
31. Al-Jami' li Ahkaamil Qur'an, oleh Imam al-Qurthubi.
32. Ahkaamul Qur'an, oleh al-Jashshash.
33. Rawaa'iul Bayan fii Tafsiri Ayatil Ahkam.
34. Lisaanul Arab, oleh Ibnu Manzhur, cet. Daar Ihyaa-it Turats al-Araby.
35. An-Nihayah fii Ghariibil Hadits, oleh Ibnul Atsiir.
36. Mufradaat Alfaazhil Qur-aan, ar-Raaghib al-Ashfahaani.
37. Shahih Sunan Abi Dawud, jilid II, oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany
[Disalin dari buku I'tikaaf, Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit Pustaka Abdullah, Gedung TEMPO Jl Utan Panjang Raya No. 64 - Jakarta Pusat, Cetakan Pertama Ramadhan 1425H/Oktober 2004M]
sumber: almanhaj.or.id